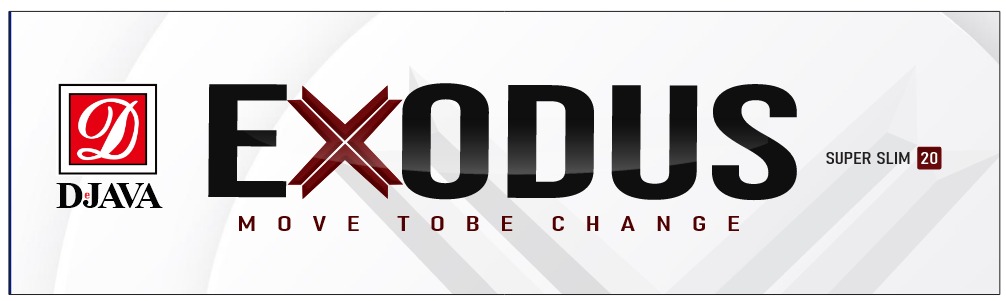OPINI | KLIKTIMES.ID – Kasus dosen yang meludahi karyawan swalayan beberapa waktu lalu menjadi sorotan publik dan memicu kecaman luas di media sosial. Peristiwa ini tidak hanya dipandang sebagai tindakan tidak sopan secara pribadi, tetapi juga mencerminkan persoalan etika yang lebih serius di ruang publik. Seorang dosen merupakan figur intelektual yang memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir, sikap, dan karakter mahasiswa. Oleh karena itu, ketika seorang dosen melakukan tindakan yang merendahkan martabat orang lain, persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kajian etika pemerintahan.
Dalam perspektif etika pemerintahan, etika tidak hanya melekat pada pejabat negara yang memiliki jabatan formal, tetapi juga pada aktor publik yang memiliki pengaruh sosial dan otoritas moral. Dosen dapat dikategorikan sebagai pejabat intelektual karena memiliki legitimasi keilmuan, status sosial, serta peran strategis dalam membentuk nilai-nilai publik. Sebagai pendidik, dosen tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi teladan dalam bersikap dan bertindak, baik di lingkungan akademik maupun di ruang publik.
Tindakan meludahi karyawan swalayan merupakan bentuk pelanggaran etika yang serius karena melanggar nilai dasar kemanusiaan, seperti penghormatan terhadap martabat manusia dan kesetaraan sosial. Dalam etika pemerintahan, setiap individu yang memiliki kekuasaan baik kekuasaan struktural maupun simbolik—wajib menggunakannya secara bertanggung jawab. Dosen memiliki kekuasaan simbolik berupa gelar akademik dan status intelektual. Ketika kekuasaan tersebut digunakan untuk merendahkan pihak lain yang posisinya lebih lemah secara sosial, maka telah terjadi penyalahgunaan otoritas moral.
Kasus ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan etika dan praktik etika. Secara teoritis, dosen memahami nilai moral, norma sosial, dan prinsip etika yang sering diajarkan di ruang kelas. Namun, pemahaman tersebut tidak selalu tercermin dalam tindakan nyata. Hal ini menjadi persoalan klasik dalam etika pemerintahan, yaitu lemahnya internalisasi nilai etika dalam perilaku sehari-hari. Etika sering kali hanya dipahami sebagai konsep normatif, bukan sebagai pedoman hidup yang benar-benar dijalankan.
Peristiwa ini menjadi refleksi penting bahwa krisis etika tidak hanya terjadi di lingkup birokrasi atau pemerintahan formal, tetapi juga di sektor pendidikan. Padahal, dunia pendidikan seharusnya menjadi fondasi utama dalam membangun etika publik. Ketika dosen sebagai aktor utama pendidikan justru menunjukkan perilaku tidak etis, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dapat menurun. Lebih jauh, kondisi ini berpotensi menormalisasi perilaku tidak etis di tengah masyarakat.
Selain itu, kasus ini memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara dosen dan karyawan swalayan. Dalam etika pemerintahan, relasi kuasa harus dijalankan dengan prinsip keadilan, empati, dan penghormatan terhadap sesama. Setiap individu, tanpa memandang latar belakang pekerjaan atau status sosial, memiliki hak yang sama untuk dihormati. Perilaku merendahkan terhadap karyawan tidak hanya melanggar etika sosial, tetapi juga bertentangan dengan nilai keadilan sosial yang menjadi dasar dalam tata kelola pemerintahan yang beretika.
Perilaku tidak etis yang dilakukan oleh pejabat intelektual juga dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kepercayaan publik. Masyarakat menaruh harapan besar pada kaum intelektual sebagai penjaga nilai rasionalitas, moralitas, dan kemanusiaan. Ketika harapan tersebut dikhianati, akan muncul sikap sinisme dan apatis terhadap dunia pendidikan. Hal ini berbahaya karena pendidikan seharusnya berperan sebagai agen perubahan sosial yang menjunjung tinggi nilai etika dan keadilan.
Dalam perspektif etika pemerintahan, kasus ini berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas moral. Akuntabilitas tidak hanya berarti pertanggungjawaban secara hukum, tetapi juga pertanggungjawaban secara etis kepada publik. Tindakan seperti permintaan maaf terbuka, pemberian sanksi etik dari institusi, serta evaluasi perilaku menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya akuntabilitas yang jelas, pelanggaran etika berpotensi dianggap sebagai hal yang wajar dan dapat terulang kembali.
Kekuasaan tidak selalu berbentuk jabatan politik atau kewenangan administratif, tetapi juga bisa berupa pengaruh sosial dan simbolik. Ketika kekuasaan tidak dikendalikan oleh etika, maka akan melahirkan tindakan sewenang-wenang dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pembelajaran etika pemerintahan harus dipahami sebagai bekal utama dalam menjalankan peran di ruang publik.
Krisis etika pejabat intelektual dalam kasus dosen meludahi karyawan swalayan menunjukkan bahwa etika masih menjadi tantangan besar dalam kehidupan publik. Etika pemerintahan menegaskan bahwa setiap aktor publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga sikap dan perilaku. Jika kaum intelektual gagal menjadi teladan, maka krisis kepercayaan publik akan semakin dalam. Oleh sebab itu, penguatan etika harus dimulai dari kesadaran individu, diperkuat oleh institusi pendidikan, dan diawasi oleh masyarakat secara kolektif agar kehidupan publik yang beretika dapat terwujud.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga menunjukkan lemahnya budaya etika di ruang publik. Masyarakat sering kali masih memandang etika sebagai urusan pribadi, bukan sebagai tanggung jawab sosial. Padahal, etika pemerintahan menekankan bahwa setiap perilaku aktor publik memiliki dampak terhadap tatanan sosial dan kualitas kehidupan bersama. Ketika tindakan tidak etis dibiarkan atau dianggap sepele, maka standar moral publik akan semakin menurun.
Selain itu, media sosial memiliki peran besar dalam mengungkap dan menyebarkan kasus pelanggaran etika seperti ini. Reaksi publik yang cepat menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap perilaku aktor publik, termasuk pejabat intelektual. Namun, kritik publik seharusnya tidak berhenti pada kecaman semata, melainkan diarahkan pada upaya pembelajaran bersama.
Kasus dosen meludahi karyawan juga memperlihatkan pentingnya integrasi pendidikan etika dalam sistem pendidikan tinggi. Etika tidak cukup diajarkan sebagai mata kuliah pelengkap, tetapi harus menjadi bagian dari budaya kampus. Perguruan tinggi perlu mendorong dosen dan seluruh civitas akademika untuk menjunjung tinggi nilai kesopanan, empati, dan penghormatan terhadap sesama. Dengan demikian, kampus tidak hanya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang pembentukan karakter yang beretika.
*) Oleh Annora Elyzia Niriko dan Elmira Madita Zahra, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang.