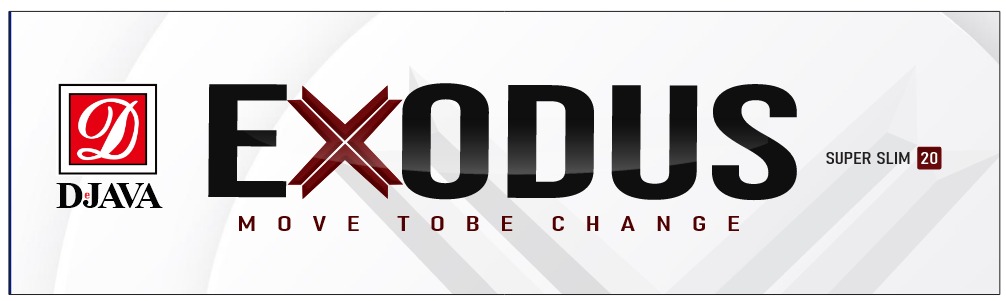OPINI, Klik Times – Tidak berlebihan jika Indonesia di juluki sebagai zamrud khatulistiwa, sebagai negara tropis, Indonesia menyimpan banyak keindahan alam yang senantiasa mengundang perhatian dari publik baik dari dalam negeri maupun luar negeri, salah satunya adalah raja ampat. Keunikan geologis dan keindahannya merupakan magnet kuat yang mengundang perhatian tersebut.
Raja ampat merupakan rumah dari berbagai hayati dan vegetasi yang hidup di kepulauannya maupun biota laut yang hidup di perairannya. Bahkan Kawasan raja ampat merupakan bagian dari daerah yang di akui sebagai UNESCO Global Geopark (Shidqi, 2023: 30).
Namun sayangnya, akhir-akhir ini raja ampat Kembali menjadi topik pembicaraan bukan karena ditemukannya varietas bioma baru ataupun penemuan arkeologis baru, namun karena adanya pemberitaan mengenai ekploitasi berupa penambangan nikel yang terjadi di daerah yang mayoritas merupakan Kawasan konservasi ini.
Kekhawatiran yang muncul dengan adanya penambangan di raja ampat ini terutama berkaitan dengan dampak ekologis dan sosial yang bersifat destruktif. Sedimentasi limbah penambangan nikel yang dibuang ke laut ditakutkan akan merusak terumbu karang dan vegitasi laut yang pada akhirnya akan merusak ekosistem di dalamnya cecara keseluruhan.
Tidak berhenti sampai disitu, Bak efek domino, efek dari kerusakan ekologis tersebut juga berdampak secara sosial ekonomi, dimana mayoritas penduduk di kepulauan raja ampat berprofesi sebagai nelayan, sehingga dengan terganggunya ekosistem laut akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari mata pencaharian mereka.
Selain di Raja Ampat, Hal serupa juga dirasakan di beberapa daerah lainnya, sebut saja di Kabupaten Bantaeng Sulawesi selatan. Menurut penelitian yang di lakukan oleh Universitas Indonesia Timur, di kawasam tersebut terdapat enam pabrik pengolahan nikel milik perusahaan asal Sanghai, Tiongkok yaitu Huadi Group. Masing-masing; PT Huadi Nickel Alloy Indonesia, PT Unity Nickel-Alloy, PT Downstone Energy Material, PT Huadi Wuzhou Nickel Industry, PT Yatai Huadi Alloy Indonesia dan PT Hengseng New Energy Material Indonesia.
Enam perusahaan itu mengolah bakan baku dari tambang di wilayah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Pulau Kalimantan (Amiruddin, et al., 2024: 324). Dampak buruk dari adanya kegiatan pengolahan nikel dapat dirasakan langsung oleh warga setempat. Seperti polusi udara yang ditandai dengan hujan debu yang menyelimuti perkampungan, asap pekat yang didalamnya terkandung konsentrasi polutan seperti Sulfur Dioksida (SO2) dan karbon Monoksida (CO) yang memengaruhi pernapasan warga.
Selain udara, pencemaran juga terjadi di lahan pertanian yang menjadi ladang mata pencaharian masyarakat setempat. Akibat dari kontaminasi limbah smelter nikel, masyarakat mengalami gagal panen, dan lahan menjadi tidak produktif. Sehingga berimplikasi pada ekonomi dan ketahanan pangan di daerah tersebut.
Narasi yang kerap kali di dongengkan oleh para pihak berkepentingan untuk mendorong ekspansi dari perusahaan penambangan dan pengolahan nikel tersebut adalah untuk “Hilirisasi Nikel” dan “Transformasi energi hijau” yang memiliki tendensi terhadap pengembangan perekonomian dan mengakselerasi pengadopsian transportasi ramah lingkungan.
Tidak dapat dipungkiri sebagai negara yang berada di zona pacific ring of fire (zona cincin apa pasifik) menyebabkan indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki potensi tambang yang sangat besar termasuk potensi tambang nikelnya. Bahkan Indonesia merupakan penyuplai timah terbesar di dunia mencapai 50,5% dari kebutuhan nikel dunia (Statista, 2024).
Hilirisasi sendiri merupakan suatu istilah yang merujuk pada proses transformasi dari industri penghasil bahan mentah (Indutri Hulu) menjadi industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi (Industri Hilir).
Dalam konteks pertambangan nikel, seperti yang telah di paparkan diatas, Indonesia merupakan negara yang menjadi salah satu negara sentra pertambangan Nikel, namun dulu, negara kita hanya mengekspor nikel mentah dengan harga yang tidak terlalu tinggi.
Oleh sebab itu, berdasarkan undang-undang nomer 3 tahun 2020 tentang perubahan nomer 4 tahun 2009 yang mengatur berbagai aspek berkaitan dengan pengembangan industri termasuk hilirisasi nikel sebagai salah satu proyek stategis nasional (PSN) yang diharapkan dapat mendongkrak laju perokonomian negara.
Secara ekonomi, hilirisasi nikel merupakan hal yang sangat menarik untuk di dorong secara serius oleh pemerintah, namun ironinya, aspek ekologi merupakan sisi yang sangat dirugikan dengan adanya proyek nasional yang telah di gaungkan sejak rezim Jokowi Dodo dan dilanjutkan oleh kabinet merah putih di bawah kepemimpinan Prabowo subianto ini.
Seperti data yang di sampaikan di atas, bahwa efek ekologis dari pertambangan dan limbah dari smelter pengolahan nikel ini kerap kali di lupakan bahkan tidak di pedulikan. Padahal denga rusaknya ekosistem akibat program pengembangan yang katanya untuk rakyat ini, pihak yang pertama kali merasakan impact-nya adalah rakyat.
Ironinya juga, adanya penambangan nikel tidak memberikan jaminan terhadap kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Pribahasa “terjatuh tertimpa tangga” mungkin pas dalam memfrasakan nasib masyarakat di sekitar tambang yangkerap kali menjadi korban karena tanahnya terkontaminasi logam berat, air dan udara yang dihirupkan penuh dengan polutan yang berbahaya bagi tubuh dan tidak mendapatkan insentif yang sepadan dari pihak-pihak terkait.
Selain landasan ekonomis, transformasi energi hijau menjadi salah satu jargon di balik masifnya pembukaan lahan dan pemberian izin tambang nikel di negeri kita. Akhir-akhir ini memang terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai atau yang dikenal sebagai electrice vehicle batrei (EVB) baik kendaraan roda dua ataupun roda empat.
Di lansir dari cnnindonesia.com, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan total populasi kendaraan listrik mencapai 133.225 unit di Indonesia sejak 2019 hingga April 2024 berdasarkan data yang ia kutip dari Kementerian ESDM.
Trend ini tidak hanya terjadi di perkotaan, namun juga di pedesaan, dibukanya sorum-sorum yang secara khusus menawarkan kendaraan yang ditenagai oleh baterai mengindikasikan meningkatnya atensi maysarakat terhadap jenis kendaraan tersebut. Kendaraan listrik memang terlihat lebih ramah lingkungan, karena tidak menghasilkan gas buang seperti kendaraan berbahan bakar petrol atau bensin.
Narasi ramah lingkungan merupakan hal yang sangat rasional untuk mendorong proses migrasi kendaraan berbahan bakar fosil ke EVB. Namun terlepas dari puncak gunung es tersebut, banyak fakta dan realita di balik produksi komponen kendaraan berbasis baterai yang jarang diketahui dan nyatanya memiliki dampak yang serius terhadap ekologi bahkan melanggar hak asasi manusia. Seperti yang dipaparkan di atas, karena salah satu bahan utama dalam produksi baterai adalah nikel yang diperoleh melalui proses penambangan, maka jika tidak di Kelola secara baik dan bijaksana akan berdampak buruk secara ekologi.
Ironinya, walaupun dalih yang di gembar-gemborkan oleh pemerintah dalam hilirisasi nikel adalah untuk mengejar produksi baterai dalam agenda transformasi energi, dan ambisi untuk menjadi pemain kunci dalam industri baterai, sayangnya hal tersebut hanyalah alasan utopis belaka karena menurut data dari U.S Geological Survey Tahun 2023, walaupun Indonesia diprediksi memiliki cadangan nikel 21 juta ton atau 42,3% cadangan nikel dunia, namun, 96,4% produk hilirisasi nikel yang dihasilkan merupakan jenis nikel kualitas rendah seperti NPI dan FeNi dengan rata- rata produksi tahunan masing-masing 861 ribu ton dan 1,18 juta ton—sebagai yang hanya berakhir menjadi bahan baku baja tahan karat.
Sedangkan nickel matte, bahan baku baterai, rata-rata hanya 80 ribu ton. Jadi, narasi yang di sampaikan oleh para pengampu kebijakan dalam hal ini hanyalah untuk mencari public trust dan membuat seolah-olah negara berkontribusi dalam permasalahan global namun ternyata, tendasi yang mencolok hanya demi kepentingan korporasi dan pihak-pihak tertentu semata.
Selain di dalam lingkup nasional, secara internasional, dengan semakin besarnya kebutuhan terhadap baterai. Menimbulkan juga suatu permasalahan berkaitan dengan isu penambangan kobalt di kongo yang dinilai sebagai bentuk perbudakan di dunia modern. Sebagai penyuplai 60% kobalt dunia, nyatanya tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya.
Politik dan ekonomi ekstraktif yang diaplikasikan di Republik Demokratik Kongo (RDK) menumbuh suburkan Artisanal Mine (tambang skala kecil) yang mempekerjakan anak-anak (child labour) dan perempuan dengan gaji $2 dollar untuk untuk setiap 12 jam nya.
Selain upah yang kecil, perempuan dan anak pekerja tambang di kongo juga banyak mengalami kekerasan seksual. Banyak diantara mereka yang merupakan warga sipil, namun diambil secara paksa dari keluarga mereka untuk dipekerjakan sebagai penambang dan sebagai pemuas hawa nafsu bagi para pemimpin yang mengoprasikan pertambangan tersebut.
Menurut data dari perwakilan centre de recherche sur I’environment, ia democratie et les droits de I’homme (CREDDHO) atau pusat riset lingkungan, demokrasi dan hak asasi manusia, anak-anak perempuan ini bekerja sebagai pekerja tambang pada siang hari, dan melayani lelaki secara seksual di malam hari.
Transformasi energi dan hilirisasi merupakan cita-cita yang sebenarnya memiliki visi progresif dalam usaha menjawab tantangan global terutama dalam mengurangi adiksi terhadap penggunaan bahan bakar berbasis petrol yang disinyalir memberikan sumbangsih besar terhadap masalah lingkungan seperti global warming (pemanasan global) dan climate change (perubahan iklim) yang efeknya dapat dirasakan secara global.
Namun usaha dalam mewujudkan transformasi dan pembangunan ekonomi ini masih menjadi paradox pembangunan, karena faktanya, semakin banyak baterai yang diproduksi untuk dijadikan sebagai sumber tenaga utama dalam kendaraan berbasis listrik maka di saat itu juga semakin banyak smelter pengolahan nikel dan bahan tambang lainnya yang menghasilkan polutan berupa limbah asap, cair ataupun padatan yang mencemari udara, air dan tanah yang lebih besar dampaknya dari pada kendaraan bermotor.
Selain itu untuk mengisi daya dari kendaraan listrik tersebut juga akan mengharuskan peningkatan kualitas dan kuantitas dari pembangkit listrik, yang mana, mayoritas dari pada pembangkit listrik yang ada masih di dominasi oleh pembangkit listrik yang juga menggunakan bahan bakar fosil seperti PLTU yang menggunakan bahan bakar batu bara.
Dari adanya fakta tersebut, maka perlu di rekonstruksikan Kembali Langkah dalam melakukan problem solving yang lebih solutif dalam menyelesaikan persoalan global seperti climate change dan global warming tanpa membuka kran masalah baru. Penambangan dan hilirisasi bukanlah hal yang salah, jika ekstraksi sumber daya alam tersebut dilakukan dengan tanpa mengesempingan persoalan ekologis dan aspek lainnya.
Selain itu, pengadopsian transformasi berbasis listrik sebagai bentuk transformasi energi hijau harus di barengi dengan proses transformasi pada pembangkit listrik yang sebelumnya menggunakan bahan bakar fosil beralih ke pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan seperti pembangkit listrik berbasis panel surya, gelombang laut, nuklir dan lain sebagainya, agar proses peralihan dari energi fosil ke energi yang lebih bersih dapat berjalan secara maksimal dan mencapai visi dan misi yang di usung secara global yaitu untuk menjaga keseimbangan dan keberlajutan dunia.
***
**) Opini Ditulis oleh Moh. Hafidz, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nurud Dhalam.
**) Tulisan artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak termasuk tanggung jawab media klik Times.id
**) Rubrik terbuka untuk umum. Panjang tulisan maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata.
**) Artikel Dikirim ke email resmi redaksikliktimes@gmail.com.
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirimkan apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi Klik Times.id.